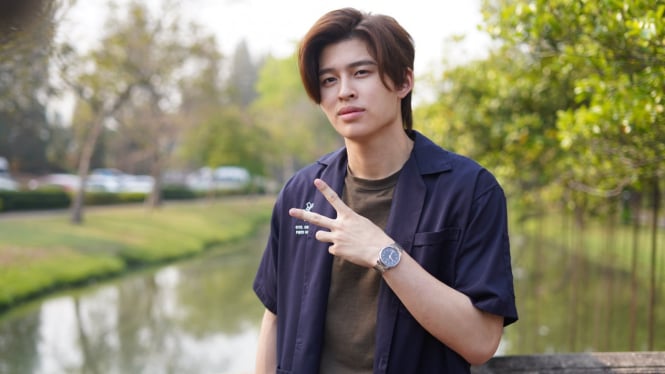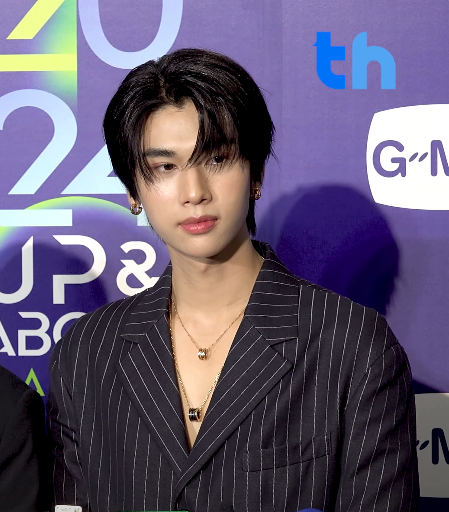Saparan adalah salah satu tradisi budaya unik Yogyakarta yang
diadakan setiap bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini merupakan ekspresi rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, keselamatan, dan hasil pertanian yang berlimpah. Saparan masih dipertahankan di berbagai daerah Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, dengan berbagai bentuk dan aktivitas yang khas di masing-masing daerah.
Tradisi ini memiliki akar budaya yang kokoh dan sering diasosiasikan dengan sejarah kerajaan, tokoh lokal, atau legenda masyarakat. Selain menjadi suatu peristiwa spiritual, Saparan juga merupakan momen untuk mempererat hubungan sosial dan kebersamaan di antara warga.
Ragam Perayaan Tradisi Saparan di Yogyakarta
Saparan Bekakak di Gamping, Sleman
Salah satu perayaan Saparan yang paling terkenal adalah Saparan Bekakak di Gamping, Sleman. Tradisi ini melibatkan prosesi penyembelihan boneka sepasang manusia dari tepung beras (bekakak) yang melambangkan sepasang suami-istri. Bekakak kemudian “disembelih” di sebuah tebing di Bukit Gamping sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh legendaris Ki dan Nyai Wono Kromo, pasangan abdi dalem yang konon meninggal tertimbun longsoran batu kapur saat melaksanakan tugas.
Prosesi ini mengandung makna pengorbanan dan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan rezeki, serta menjadi simbol untuk menolak bala. Ribuan warga dan wisatawan datang untuk menyaksikan peristiwa ini setiap tahunnya. Selain itu, acara ini juga diwarnai dengan kirab budaya, pentas seni, dan pasar rakyat.
Saparan di Wonokromo dan Gunungkidul
Di daerah Wonokromo, Pleret, Bantul, Saparan dirayakan dengan tradisi kenduri massal dan pembagian makanan tradisional seperti apem dan jenang. Warga saling membantu dalam menyiapkan makanan dan kemudian berkumpul untuk berdoa bersama. Ini menjadi simbol kebersamaan dan nilai gotong royong yang sangat dihargai dalam budaya Jawa.
Sementara itu, di Gunungkidul, Saparan juga dirayakan dengan pertunjukan reog, jatilan, dan wayang kulit, menjadikan tradisi ini tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga sebagai sarana hiburan masyarakat. Acara ini menunjukkan keberagaman budaya lokal yang terus hidup berdampingan dengan tradisi keagamaan.
Makna dan Nilai Budaya dalam Tradisi Saparan
Syukur, Keselamatan, dan Kebersamaan
Makna utama dari tradisi Saparan adalah ungkapan syukur atas kehidupan yang telah dijalani. Dalam filosofi Jawa, bulan Sapar diyakini sebagai bulan yang kurang baik jika tidak diiringi dengan doa dan syukuran. Oleh karena itu, warga mengadakan kenduri, pertunjukan seni, dan prosesi adat agar terhindar dari bahaya.
Saparan juga memperkuat tali persaudaraan antarwarga. Semua kalangan—tua, muda, pria, wanita—ikut serta dalam persiapan dan pelaksanaan. Nilai gotong royong dan kebersamaan inilah yang membuat tradisi ini tetap bertahan hingga kini.
Pelestarian Tradisi Lokal
Di tengah arus modernisasi, tradisi Saparan tetap dijaga sebagai identitas budaya lokal. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga generasi muda terus dilibatkan dalam pelestarian. Bahkan saat ini, beberapa desa menjadikan Saparan sebagai acara tahunan wisata budaya yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.